Beyond the Scientific Way
Belajar Menjadi Guru, Dosen, Widyaiswara, Ustadz …
Friday, January 4th, 2013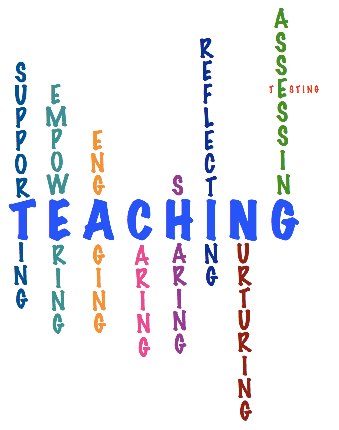 Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Apa yang sangat menginspirasi dari guru Anda itu?
Guru adalah salah satu profesi yang paling dikenal anak-anak. Sangat banyak anak punya cita-cita jadi guru, selain mungkin jadi dokter, insinyur atau pilot. Tetapi ketika mereka semakin besar, semakin kenal dengan kenyataan kehidupan guru, semakin sedikit yang masih mempertahankan cita-cita ini. Baru akhir-akhir ini saja, profesi guru “booming” lagi. Itu setelah di berbagai daerah, guru mendapat tunjangan profesi 1x gaji. Akibatnya, FKIP di berbagai kampus menjadi favorit, bahkan di beberapa kampus, persaingannya mengalahkan FT atau FE.
Sejujurnya, saya termasuk yang tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Kalau jadi ilmuwan ya. Tetapi ternyata perjalanan hidup saya menyebabkan saya melewati fase menjadi guru, juga dosen, widyaiswara, dan bahkan ustadz 🙂 Walaupun semua mungkin pakai embel-embel “Luar Biasa”.
Saya pertama kali “pura-pura” jadi guru, itu kelas 2 SMP, ketika di sekolah, guru sejarah saya mencoba menerapkan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Anak-anak diminta membentuk kelompok @ 4 orang, lalu masing-masing diberi tugas suatu bab di buku paket, lalu “mengajar” siswa yang lain di depan kelas, bahkan sampai memberikan test. Tetapi seingat saya tidak semua kelompok sempat maju, karena waktu keburu habis. Saya beruntung termasuk yang sempat tampil, bahkan saya yang didaulat untuk yang berdiri mengajar di depan kelas.
Setelah itu ternyata saya jadi sering “mengajar” untuk berbagai hal yang lain. Mengajar PKS (Patroli Keamanan Sekolah), lebih tepatnya mungkin disebut Melatih. Sebelumnya saya dan beberapa kawan dilatih menjadi anggota PKS oleh Polres. Tugas PKS itu yang terpenting seperti Polantas, tetapi khusus untuk menyeberangkan anak-anak sekolah di depan sekolah. Maklum tenaga polisi saat itu dirasa terbatas. Setelah itu, beberapa kali seminggu, pagi pukul 6.30 kami sudah bertugas. Setelah praktek beberapa bulan, sekolah merasa perlu regenerasi, sehingga kami melatih adik-adik kelas.
Setelah PKS, pengalaman menjadi “guru” yang lebih panjang ada di Pramuka dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) di SMA. Walaupun kalau direnung-renungkan sekarang, banyak “pelajaran” di Pramuka saat itu yang “nggak mutu”, tapi dulu koq ya percaya diri saja ya … he he … Kalau KIR agak mending. Sampai sekarangpun saya kira masih banyak pelajaran yang relevan, bahkan tidak cuma untuk siswa SMA, bahkan untuk sarjana yang lagi meniti karier jadi peneliti muda 🙂
Sewaktu saya kuliah di Austria, saya juga punya pengalaman beberapa kali jadi “guru”. Pertama “guru” internet. Ini terjadi tahun 1995, sewaktu penggunaan internet masih relatif awal. Mungkin ini lebih tepat disebut “tutorial”. Kedua tahun 1996, “guru” bahasa Indonesia untuk orang asing. Ternyata rumit juga mengajar bahasa Indonesia yang sistematis untuk orang bule. Murid-murid saya saat itu ada 3 kelompok motivasi. Pertama yang motivasinya pekerjaan, yakni mereka akan dikirim bekerja di Indonesia (biasanya teknisi atau personil bisnis pariwisata). Kedua yang motivasinya travelling. Ada murid saya yang profesinya Profesor Fisika, tetapi hobby travelling, dan liburan mendatang ingin “blusukan” mengelilingi Indonesia. Alamak, waktu itu saya juga belum pernah keliling Indonesia. Yang lucu yang ketiga, motivasinya keluarga. Ada murid saya, wanita Austria yang akan menikahi pria Indonesia. Jadi dia perlu belajar banyak hal agar keluarganya harmonis.
Tahun 1997, sepulang dari Luar Negeri, beberapa saat lamanya saya diminta mengajar di sebuah kursus programming di suatu perusahaan. Mereka minta diajar programming dalam Visual Basic. Sejujurnya, saat saya meng-iyakan, saya belum pernah lihat Visual Basic. Saya memang punya pengalaman programming yang cukup panjang dalam C, Pascal, Fortran, Lisp, SQL dan Basic. Tetapi Visual Basic? Akhirnya saya praktis hanya menang 1 minggu dari peserta. Tetapi alhamdulillah dalam waktu singkat saya sudah lumayan expert. Repotnya ketika di akhir kursus, ada peserta yang tanya, apakah saya sudah punya “Microsoft Certified Programmer” ? Saya menjawab diplomatis, “Sepertinya Bill Gates juga belum punya tuh? ” 🙂
Karena saya sudah mengantongi gelar Doktor, maka mulailah saya beranjak dari “guru kursus” ke dosen. Ada prodi S1 suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meminta saya masuk dalam tim dosennya. Teorinya, kalau saya masuk, ijazah S3 dan sejumlah publikasi saya bisa mendongkrak nilai akreditasi BAN-PT untuk prodi di PTS tersebut. Ternyata betul. Bahkan waktu itu, prodi di PTS tersebut terakreditasi lebih dulu dari PTN pembinanya !!! Tetapi setelah terakreditasi, tiba-tiba jumlah mahasiswa yang diterima PTS itu berlipat 3x. Dosennya yang kewalahan. Kalau cuma mengajar sih mungkin tidak terlalu berat. Tetapi kalau harus mengoreksi tugas, wow … capek dech … Apalagi mengajar di LCU (Low Cost University) ini harus lebih banyak ibadahnya … 🙂 Lima tahun kemudian, karena saya semakin sibuk di kantor, saya makin mengurangi jam mengajar saya di PTS tersebut, sampai akhirnya off sama sekali.
Saat itu saya juga mencoba menjadi dosen program S2 di IPB dan di UPM (Universitas Paramadina Mulya). Yang S2 di IPB ini program internasional, wajib pakai bahasa Inggris. Sedang yang di UPM kelas eksekutif, jadi kuliahnya malam. Sangat berbeda dengan S1, menjadi dosen S2 jauh lebih “santai”. Mahasiswanya tidak banyak, tetapi honornya banyak … he he … Kadang saya berpikir, jangan-jangan honor saya ngajar S2 ini sebenarnya untuk jerih payah ngajar S1 di LCU itu … 🙂 Yang jelas, ndosen di S2 bersama para eksekutif itu membuat kita jadi terus terasah. Kita mengakumulasi berbagai pengalaman dan wawasan.
Meski menjadi selingan yang menggairahkan, tetapi karena saya secara resmi bukan dosen, maka kadang-kadang tugas ini sedikit “terganggu”. Yang paling ringan adalah ketika tiba-tiba ada jadwal rapat yang berdekatan dengan jadwal mengajar. Kadang-kadang sulit kita mencari waktu pengganti. Yang lebih repot lagi adalah ketika kita punya atasan yang kurang suka atau bahkan tidak setuju kita “ndosen” pada jam kerja. Dianggapnya itu buang-buang waktu, atau bahkan “korupsi waktu”. Padahal sesungguhnya, pada saat mengajar, kita juga bertambah ilmu, dan juga memperluas jejaring, yang juga memiliki multiplier effect pada tugas-tugas kita di kantor. Mahasiswa S2 itu berasal dari berbagai daerah, berbagai lembaga, juga berbagai profesi dan latar belakang.
Ada beberapa kampus yang secara tersirat menawari saya pindah, jadi dosen full-time saja di sana. Mereka mengatakan, kalau jadi dosen full-time nanti bisa jadi Professor. Waktu itu saya coba hitung-hitung angka kredit kumulatif saya kalau dihitung sebagai dosen. Ternyata jauuuh. Terutama karena saya tidak bisa memenuhi porsi tri-darma perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan/pengajaran. Ya maklum, ngajar di sana-sini cuma 2 SKS. Paling total cuma 6 SKS per semester … Kalau mau “ngebut”, mesti menulis buku ajar. Sebenarnya menulis buku ajar tidak terlalu susah, karena tidak harus penemuan sendiri. Bisa menggubah ulang apa yang pernah ditulis orang lain. Tetapi sepertinya saya nggak bisa menuliskan sesuatu yang tidak pernah saya dalami sendiri. Untunglah, kemudian muncul SKB Mendiknas-Kepala LIPI-Menpan yang mengesahkan adanya Profesor Riset, yakni jenjang Professor yang menjadikan riset sebagai komponen utama.
Selain itu, untuk berbagai diklat dari berbagai kementerian/lembaga saya juga diminta menjadi “Widyaiswara Luar Biasa”. Widyaiswara agak berbeda dengan dosen, karena yang dididik bukan mahasiswa (apalagi mahasiswa S1), tetapi orang dewasa yang kadang merasa sudah lebih berpengalaman, atau bahkan merasa “untuk apa harus ikut diklat lagi, toh sudah tua dan sebentar lagi pensiun”. Jadi perlu pendekatan yang berbeda, bahasa kerennya “Andragogi”, bukan “Pedagogi”. Di diklat yang diadakan Bakosurtanal/BIG, saya kadang menjadi WLB untuk bidang Pemetaan, Penegasan Batas, Penataan Ruang, Penanggulangan Bencana dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Di LIPI saya menjadi WLB Diklat Fungsional Peneliti tingkat Lanjut. Jadi WLB ini tidak terlalu stress, karena kita cukup banyak cerita dari pengalaman kita saja, dan gak usah bikin soal yang rumit seperti ujian mahasiswa. Biasanya sih – asal tidak keterlaluan – semua peserta diklat akan lulus. Toh terserah mereka, apakah ilmu yang kita berikan akan terpakai atau tidak pada lingkup pekerjaan mereka.
Yang terakhir setelah guru – dosen – widyaiswara, itu adalah ustadz. Ini seharusnya pos yang paling tinggi. Di Mesir itu, lulusan S1 syari’ah tidak langsung dipanggil Ustadz, tetapi “Mu’id”. Nanti kalau sudah S2, dia akan dipanggil “Musaid Mudaris”. Setelah S3 dipanggil “Mudaris”. Setelah mengajar dan riset kira-kira 5 tahun, akan dipanggil “Musaid Ustadz”. Baru setelah 10 tahun sejak S3, kalau angka kumnya tercapai dan senat setuju, akan dipanggil “Ustadz”. Jadi rupanya Ustadz itu sama dengan Professor. Tetapi di Indonesia, panggilan Ustadz bisa dicapai siapa saja. Sangat egaliter. Dan tahukah Anda, bahkan sejak saya masih SMP, saya sudah dipanggil “Ustadz” !!! Itu terjadi lantaran saya membantu mengajar membaca al-Qur’an belasan anak-anak kecil di masjid kampung. Kemudian menggantikan ayah saya yang wafat mengisi majlis taklim Ibu-ibu. Kemudian mengisi khutbah di sekolah. Tentu saja, sebagai “Ustadz” tingkah laku kita lalu juga jadi sorotan. Tapi ini bagi saya tidak masalah. Ketika saya pada usia 26 tahun sudah naik haji, tambah disorot lagi !!! Karena banyak orang yang menunda naik haji, karena takut nggak bisa “membuat dosa” lagi … Itu tanda orang yang kurang cerdas. Karena, kata Imam Ghazali, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati, dan kematian bisa datang kapan saja, tidak nunggu tua. Karena itu, ayo buruan jadi “Ustadz” — mumpung di Indonesia belum perlu syarat macam-macam seperti di Mesir – asal tahu diri saja kapasitas ilmunya … 🙂
Tapi fenomena “Ustadz TV” atau “Ustadz Google” akhir-akhir ini memang agak memprihatinkan. Seorang dianggap ustadz hanya oleh aktivitas ceramahnya, dan bahannyapun “cuma disedot dari Google”. Padahal aktivitas Ustadz – dan juga guru/dosen/widyaiswara pada umumnya – yang hakiki itu adalah MENGUBAH (CHANGE). Mengubah dari mindset (pola pikir), kemudian behaviour (perilaku), dari yang kurang cerdas menjadi cerdas, dari yang kurang cekatan menjadi cekatan, dan dari yang kurang islami menjadi islami – sesuai syari’ah. Percuma saja ngustadz di TV, ditonton jutaan orang, kalau tidak satupun yang berubah, karena isinya cuma banyolan. Lebih gawat lagi, kalau isinya memang mengubah, tetapi malah mengubah jadi makin tidak islami. Karena orang yang tersesatkan akan berkilah, “Lho ini kata Ustadz Fulan di TV hukumnya halal koq”. Padahal “fatwa halal” Ustadz Fulan itu ternyata cuma pakai “dalil perasaan”, kalau tidak “katanya” ya “pokoknya”.
Baik guru, dosen, widyaiswara maupun ustadz, semua memiliki tanggungjawab sampai akherat sana. Karena itu beruntunglah mereka yang memposisikan semua amal itu untuk ibadah, bukan sekedar untuk mencari penghidupan. Kita tidak usah risau dengan kompensasi yang kadang tidak sesuai dengan jerih payah, karena “Gusti Allah ora sare” (Tuhan tidak pernah tidur). Dia Yang Maha Adil tidak akan pernah membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Hal Jazaa’ul Ihsani Illal Ihsan”.
Salam.
 Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di
Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di